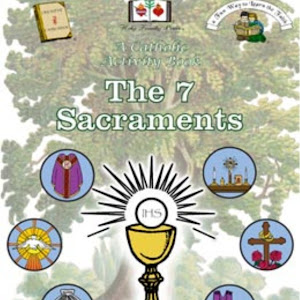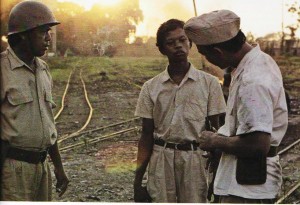FILM – tulis André Bazin (1918-1958) dalam esainya
Qu’est-ce que c’est un cinema? — lahir bukan karena hasil perkembangan teknologi rekam. Melainkan, tegas kritikus film dan pencetus jurnal
Cahier du Cinéma ini—
film itu sengaja dibuat, menjadi ada dan bisa ditonton lebih karena
“ambisi” dan pikiran sutradara yang kebelet merekam situasi sosial
dengan bantuan gambar, gerak, suara, dan omongan antarmanusia. Dengan
gagasan ini, Bazin sebenarnya mau mengatakan, nafas sebuah film lebih
bermuara pada sang sutradara daripada hal-hal lainnya.
Film Soegija memang mendapat
sambutan luar biasa dari para penontonnya. Tak kurang, di ujung
pementasan selalu diimbuhi tontonan ekstra berupa tepuk tangan meriah.
Animo umat menyaksikan karya seni bidang media film ini sungguh
membanggakan. Tiada lain karena tokoh film ini adalah Mgr. Albertus
Soegijapranata SJ, Uskup Indonesia pribumi pertama yang memangku jabatan
sebagai Uskup Danaba di Vikariat Apostolik Semarang (1940-1963).
Sedikit sosok Mgr. Albertus Soegijapranata SJ
Tapi Soegija tidak serta merta
bercerita banyak tentang sosok pahlawan nasional dengan sesanti abadinya
yang tersohor ini: “100 % Katolik, 100 % Indonesia”. Melihat sosok
Monsinyur Soegijapranata SJ dan kiprahnya menjaga integritas
nasionalisme Indonesia di kala usianya masih balita tentu tidak pernah
akan lengkap, kalau hanya bermodalkan 2 jam menikmati Soegija di layar lebar.
Soegija –nama kecil Mgr. Albertus
Soegijapranata SJ ketika masih frater Jesuit—jelas lebih agung, heroik,
dan tentu saja juga lebih hebat daripada sekedar Soegija hasil
besutan sutradara Garin Nugroho. Membaca paparan studi ilmiah Romo Dr.
Gregorius Budi Subanar SJ dalam tiga buku serial tentang sosok Romo
Kandjeng ini, sudah pastilah Soegija dalam bentuk seluloid ini
kalah lengkap dibanding apa yang telah dilakukan Romo Kandjeng dalam
panggung riil berupa konteks sosial politik Indonesia sebelum dan pasca
Kemerdekaan RI.
Nah, film Soegija pada hemat
saya kurang tegas mengambil tema besar dengan lebih memfokuskan diri
pada sepak terjang perjuangan Mgr. Albertus Soegijapranata SJ (Nirwan
Dewanto) menjaga wibawa nationhood Indonesia yang waktu itu itu hendak dikangkangi oleh Jepang dan kemudian Belanda.
Soegija pada hemat saya justru
banyak berkisah tentang romansa seorang perawat nasionalis bernama
Mariyem (Anissa Hertami) yang ditaksir berat oleh fotografer Belanda
Hendrick van Maurick (Wouter Braaf). Juga pada sisi lain, kisah
terpisahnya Lingling (Andrea Reva) dari pelukan ibunya (Olga Lydia) dan
tentu saja nafsu gila komandan tentara Belanda Robert (Wouter Sweers)
yang selalu menganalogikan dirinya sebagai mesin perang.
Sekali lagi, mengikuti alur pikir André Bazin di atas, Soegija
akhirnya menjadi kurang gagah lantaran terlalu mengikuti “logika”
skenario garapan penulis naskah dan alur cerita arahan sang sutradara.
Jadi, sebagai penonton saya memang sedikit kecewa karena sosok Mgr.
Albertus Soegijapranata nyaris “digilas” habis oleh kisah romansa, deru
dan tragedi perang, serta konflik batin manusia yang merobek nurani para
pemuda nasionalis, termasuk komandan pasukan bela diri Jepang.
Sekali waktu seorang romo Jesuit yang tahu seluk-beluk proses produksi film Soegija ini secara personal berkisah pada Redaksi Sesawi.Net
–katanya—hasil riset mendalam yang dikerjakan Romo Budi Subanar SJ
tentang sosok Mgr. Albertus Soegijapranata ternyata kurang banyak muncul
dalam sosok Soegija besutan Garin Nugroho.
Namun, sejujurnya saya pun sangat terhibur bisa menikmati film Soegija
itu justru karena sejak awal tidak mengambil sikap dalam kerangka pikir
ingin mempersepsi tontonan layar lebar itu sebagai sebuah “dokumen
sejarah”.
Seakan mengikuti “logika” pasar, maka agar lebih menarik film Soegija pun lalu dikemas dengan sedikit agak kenes dan siapa tahu pasar pun diharapkan juga akan merespon positif. Jadi mahfum juga kalau seorang batur plus koster Toegimin (Butet Kertaradjasa) berani nranyak geguyonan (kelewatan
bercanda) dalam bertutur kata dengan Romo Kandjeng –hal yang rasanya
muskil ada dalam peta sosial waktu itu dimana seorang Uskup terlalu
“besar” dan berwibawa untuk umat sekalipun, apalagi di mata seorang
pembantu. (Bersambung)
sumber : http://www.sesawi.net/